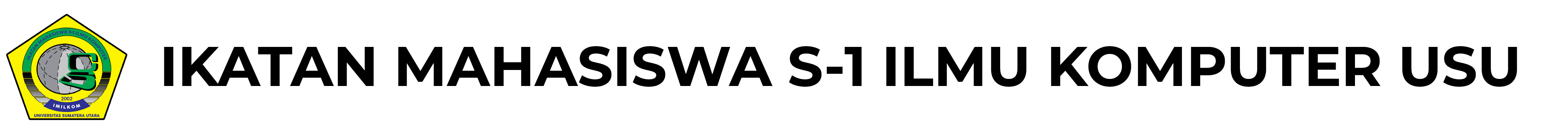Gratis yang Mahal: Berapa Sebenarnya Biaya ChatGPT?
ChatGPT sering dipromosikan sebagai teknologi “gratis” cukup buka browser, ketik pertanyaan, dan jawaban muncul dalam hitungan detik. Tapi di balik kemudahan itu, ada biaya nyata yang jarang dibicarakan: listrik. Bukan sedikit, dan bukan abstrak. Setiap kali seseorang mengirim satu prompt ke ChatGPT, server di data center raksasa harus bekerja, memproses, dan mendinginkan mesin-mesin komputasi berdaya tinggi.
Menurut estimasi terbaru, satu query ChatGPT mengonsumsi sekitar 0,34 watt-hour (Wh) pada versi yang lebih efisien, atau hingga 2,9 Wh dalam estimasi konservatif. Sebagai perbandingan, Google Search hanya mengonsumsi sekitar 0,03 Wh per pencarian. Artinya, satu pertanyaan ke ChatGPT bisa 10 kali lebih boros energi dibandingkan pencarian Google biasa. Dalam analogi sehari-hari, satu query ChatGPT kira-kira setara dengan menyalakan oven listrik selama sekitar 10 detik—terlihat sepele, sampai skalanya menjadi global.
Skala itulah yang mengubah “gratis” menjadi mahal. Pada Desember 2025, ChatGPT diperkirakan memiliki 810 juta pengguna aktif mingguan, dengan sekitar 2,5 miliar query per hari secara global. Jika dikalikan, konsumsi hariannya mencapai sekitar 850 megawatt-hours (MWh) cukup untuk mengisi daya ribuan mobil listrik Tesla setiap hari. Dalam setahun, total konsumsi energinya mencapai 17.228 gigawatt-hours (GWh), setara dengan listrik untuk sekitar 1,64 juta rumah tangga di Amerika Serikat.
Angka itu juga setara dengan konsumsi listrik tahunan negara seperti Puerto Rico, Slovenia, atau Kenya. Untuk sebuah layanan yang sering disebut “gratis”, jejak energinya justru setara dengan satu negara.
Tagihan Listrik yang Melonjak, Dari Amerika hingga Asia
Konsumsi energi besar itu tidak menghilang begitu saja. Ia masuk ke jaringan listrik nasional, memengaruhi pasokan, dan pada akhirnya tercermin dalam tagihan listrik masyarakat. Di Amerika Serikat, negara bagian yang menjadi pusat pertumbuhan data center mulai merasakan dampaknya. Di Maryland, rata-rata rumah tangga melihat kenaikan tagihan sekitar 18 dolar AS per bulan, sementara di Ohio sekitar 16 dolar AS per bulan. Angka ini mungkin tampak kecil, tetapi bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah, itu berarti pengeluaran tambahan ratusan dolar per tahun.
Di area yang lebih dekat dengan data center, dampaknya jauh lebih tajam. Harga listrik grosir di beberapa wilayah melonjak hingga 267 persen, terutama di daerah yang menjadi klaster data center. Studi menunjukkan bahwa sekitar 70 persen kenaikan harga listrik terjadi dalam radius 50 mil dari fasilitas data center. Dengan kata lain, mereka yang tinggal paling dekat dengan “otak digital” dunia justru menanggung beban paling berat.
Fenomena ini tidak terbatas di Amerika. Di Jepang, harga lelang listrik mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, didorong oleh lonjakan permintaan industri, termasuk data center. Di Malaysia, pemerintah mengumumkan kenaikan tarif listrik sebesar 13,6 persen, dari 39,95 sen menjadi 45,40 sen per kWh kenaikan yang secara langsung dirasakan rumah tangga dan usaha kecil. Di Inggris, proyeksi jangka panjang menunjukkan kenaikan tarif hingga 9 persen pada 2040, sebagian dipicu oleh pertumbuhan kebutuhan listrik digital.
Bayangkan sebuah keluarga yang tidak pernah menggunakan AI, tidak berlangganan layanan cloud premium, dan hanya memakai internet untuk kebutuhan dasar. Ketika tagihan listrik mereka naik drastis, jarang ada penjelasan bahwa sebagian beban itu datang dari data center yang melayani miliaran prompt AI setiap hari bukan dari konsumsi mereka sendiri.
Follow the Money: Siapa Untung, Siapa Rugi?
Untuk memahami krisis ini, kita perlu mengikuti aliran uang. Perusahaan teknologi besar mendapatkan nilai ekonomi luar biasa dari AI generatif: peningkatan produktivitas, produk baru, dan valuasi pasar yang melonjak. Perusahaan utilitas listrik juga diuntungkan melalui kontrak pasokan energi jangka panjang bernilai miliaran dolar. Namun di sisi lain, masyarakat umum membayar melalui tarif listrik yang lebih tinggi dan tekanan pada jaringan energi nasional.
Ironinya, subsidi tidak langsung ini bersifat regresif. Mereka yang paling sering menggunakan AI perusahaan besar, startup teknologi, dan pengguna berat bukanlah satu-satunya yang membayar biaya energinya. Mereka yang tidak menggunakan AI sama sekali tetap terkena dampaknya. Ini menciptakan trade-off yang tidak adil: manfaat terkonsentrasi pada segelintir pihak, sementara biayanya disebar ke seluruh populasi.
Situasi ini juga mulai merambah ranah politik. Di berbagai negara, janji untuk menahan atau menurunkan tarif listrik menjadi pesan kampanye yang kuat. “Saya akan membekukan harga listrik,” adalah kalimat yang terbukti ampuh menarik suara. Namun janji itu berbenturan dengan realitas: permintaan listrik dari data center dan AI terus tumbuh, dan tanpa perubahan struktural, tekanan harga sulit dihindari.
Seorang analis energi merangkum dilema ini dengan lugas: “Data center melahap listrik dan air, tapi mereka juga menjadi fondasi kenyamanan modern. Pertanyaannya bukan apakah kita membutuhkannya, tetapi siapa yang harus membayar.”
2030: Dunia yang Lebih Lapar Energi
Jika tren saat ini berlanjut, gambaran masa depan terlihat lebih menantang. Pada 2030, total konsumsi energi AI diproyeksikan mencapai 347 TWh, melonjak tajam dari sekitar 15 TWh pada 2025. Jumlah query global diperkirakan mencapai 329 miliar per hari, setara dengan 38 query per orang di Bumi setiap hari. AI tidak lagi menjadi alat tambahan, melainkan lapisan dasar dalam kehidupan digital sehari-hari.
Di Amerika Serikat, data center diperkirakan akan menyumbang hampir 50 persen pertumbuhan permintaan listrik nasional dalam dekade mendatang. Di Jepang, lebih dari 50 persen pertumbuhan permintaan listrik dikaitkan dengan data center, sementara di Malaysia angkanya mencapai lebih dari 20 persen. Angka-angka ini menunjukkan bahwa AI bukan sekadar isu teknologi, tetapi isu infrastruktur dan kebijakan publik.
Apakah ini gelembung yang suatu hari akan pecah, atau realitas baru yang harus kita terima? Banyak pakar berpendapat bahwa permintaan tidak akan turun, tetapi efisiensi dan sumber energi yang harus berubah. Tanpa pergeseran besar ke energi terbarukan dan desain sistem yang lebih hemat daya, tekanan pada jaringan listrik hanya akan meningkat.
Pertanyaan yang Harus Dijawab
Pada akhirnya, ironi terbesar dari ChatGPT dan AI generatif adalah label “gratis”-nya. Layanan ini mungkin tidak meminta kartu kredit, tetapi biayanya nyata dan dibayar bersama-sama melalui tagihan listrik, pajak, dan tekanan lingkungan. Seperti mengemudi ke restoran favorit sekali setahun terasa ringan bagi satu orang, tetapi jika dilakukan oleh miliaran orang secara bersamaan, dampaknya menjadi masif.
Teknologi selalu membawa trade-off. AI menawarkan efisiensi, kreativitas, dan kemudahan yang belum pernah ada sebelumnya. Namun krisis listrik yang menyertainya memunculkan pertanyaan tentang keadilan distribusi biaya. Apakah adil jika mereka yang tidak pernah menggunakan AI tetap membayar harga energinya? Haruskah perusahaan teknologi menanggung porsi biaya yang lebih besar? Atau akankah masyarakat terus mensubsidi kenyamanan digital tanpa benar-benar menyadarinya?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang jarang muncul di halaman promosi teknologi. Tapi di tengah lonjakan tagihan listrik global, pertanyaan itu semakin sulit diabaikan. Jika ChatGPT benar-benar “gratis”, mungkin saatnya kita bertanya: gratis untuk siapa, dan dibayar oleh siapa?